
ROMANTISME NAIF GAYA Ahlusunnah Waljama'ah
Tantangan keberagaman saat ini memasuki babak baru. Kalau pada beberapa dekade yang lalau uat beragama masih berkutat untuk saling membuktikan bahwa agamanya yang paling benar dan agama orang lain salah, maka keberagamaan saat ini sudah melampui klaim benar-salah tersebut. Orang tidak ingin lagi terjebak pada truth claim yang dalam sejarah kemanusiaan ternyata melahirkan kekerasan dan penistaan kemanusiaan yang hampir-hampir tidak bisa di nalar oleh logika agama itu sendiri. dalam arti bahwa agama yang dalam dirinya memuat nilai-nilai luhur penghormatan nilai-nilai kemanusia –agama untuk manusia- ternyata seringkali menampilkan wajah yang sebaliknya.
Kesadaran ini tidak mesti di pahami sebagai humanisme naif yang diawali oleh gerakan rennaisance, tapi bahwa kemanusiaan sebuah agama harus bisa di ukur apakah ia dapat mengankat menuasia pada derajat kesempurnaannya ataukan tidak. Sejalan dengan ini, maka agama tidak seharusnya alasan untuk bertindak yang justru menginjak-injak human digniti. Jadi, adagium “agama untuk manusia” harus dipahami bahwa dengan agama, manusia semestinya menemukan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, baik secara individual manupun koleketif. Jadi, bukan dalam pengertian humanisme naif yang meletakkan manusia sebagai titik pusat kosmos sambil merasa berhak untuk melakuakan apapun tanpa mempedulikan keseimbangan tatanan kosmos.
Kesadaran ini akhirnya melahirkna gugatan-gugatan terhadap tafsir-tafsir keagamaan yang selama ini di rasa sering menjadi tidak masuk bagi tindak-tindak yang manusiawi. Tidak perlu di tutup-tutupi bahwa seringkali tafsir keagamaan memainkan peranan penting dalam konflik-konflik kemanusiaan. Sejarah Perang Agama di Eropa yang hampir melumpuhkan Eropa terjadi karena tafsir agama ini. Begitu juga dengan pembelahan umat umat Islam hingga saat ini antara Sunni dengan dari syii yang seringkali menjadi konflik terbuka dan terang-terangan juga dipicu dari sebab yang sama. Dari sini menyadarkan kita bahwa tafsir keagamaan telah begitu banyak andilnya dalam menentukan peradaban manusia. Karena begitu signifikansi posisinya inilah, maka proses evaluasi menjadi perlu untuk selalu digerakkan jika kita tidak ingin peradapan kita hancur justru karena klaim – klaim normatif agama.
Kesadaran inilah yang saya kira membuat kita juga merasa legitimate untuk menilai ulang doktrin Ahlusunnah Waljama'ah yang sekian lama selalu selalau dijadikan ukuran baka untuk menilai kebenaran dan kesalahan seseorang atau kelompok dalam ber-isla. Berkaitan dengan ini pula, seluruh tantangan – tantangan kemanusiaan yang datang dan menantang di depan mata kita hendak kita benturkan dengan konsep Ahlusunnah Waljama'ah. Seperti yang ditulis oleh Gus Mus, bahwa keresahan yang bernada tuntutan tidak lagi bisa dibendung. Petanyaan itu misalnya bagaimana sikap Ahlusunnah Waljama'ah dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan sosial, dalampolitik, ekonomi, budaya, dsb? Pembicaraan kita kali ini juga berada diatas rel yang sama (on the same track) dengan tuntutan – tuntutan di atas. Topik “Ahlusunnah Waljama'ah sebagai Manhajul al-Fikr dalam perspektif sosial, budaya, HAM dan lingkungan” adalah sebuah topik yanghendak menuntut Ahlusunnah Waljama'ah untuk menjawab problem – problem kemanusiaan kontemporer yang kurang – lebih adalah poin – poin tersebut.
Akan tetapi, sebelum kita melanjutkan upaya untukmejawab tuntutan tersebut, yang perlu kita pertanyakan adalah apakah tuntutan tersebut proporsional atau nyinyir? Barang kali justru pertanyaan inilah yang perlu kita selesaikan dulu. Jangan – jangan tuntutan ini semacam sikap romantis yang terlanjur mengidealisasi Ahlusunnah Waljama'ah sebagai pusat kebeanaran dalam ber – islam sehingga seluruh problem kemanusiaan harus bisa dijelaskan dalam kerangka Ahlusunnah Waljama'ah –Aswajamania. Kalu memmang ya. Lau, apa bedanya kita dengan para apolog muslim naif yang terus berkoar – koar bahwa seluruh persoalan telah tuntas di jawab oleh Al-Quran sambil menuntut semua orang untuk mengikutinya. Sebuah sikap yang ujung –ujungnya anti toleran, anti pluralitas dan menista HAM. Kalu kita justru terjebak disini, tentu sebuah ironi karana toleransi, penegakan HAM dan liberasi adalah sebuah idealita yang hendak kita perjuangkan.
Ahlusunnah Waljama'ah : Relasi –Relasi Kuasa “We” dan “Other”
Pertanyaan pertama yang patut kita lontarkan disini adalah apakah benar – benar ada Ahlusunnah Waljama'ah dan non –Ahlusunnah Waljama'ah. apakah kolompok non-Ahlusunnah Waljama'ah yang diidentifikasi selama ini sesuai dengan direpesentasikan oleh kelompok Ahlusunnah Waljama'ah?pertanyaan ini sesungguhnya mengandaikan bahwa pencitraan yang dilakukan oleh kelompok Ahlusunnah Waljama'ah adalah sebuah konsep yang diturunkan dari kajian akademis,tapi juga kumpulan imagi –imagi tentang kelompok yang sesat .Di dalam Ahlusunnah Waljama'ah berkumpul sejumlah kode,vocubulari serta praangapan –praanggapan yang menjadi teks pengikat terhadap siapa saja yang hendak melihat dan menilai apa yang disebut sebagai kelompok non Ahlusunnah Waljama'ah .Ahlusunnah Waljama'ah tidak berurusan dengan kesesuaian klaim –klaimnya dengan kenyataan yang ada ,tapi berurusan dengan konsistensi internal dengan ide-idenya tentang kelompok non Ahlusunnah Waljama'ah yang sesat tanpa harus beruruasan dengan realitas yang sesungguhnya.
Terdapat obyek khas yang hanya diciptakan pikiran sehingga obyek yang sebenarnya fiktif berubah memperoleh status obyektif. Sekelompok orang yang hidup di tempat tertentu akan mnciptakan batas-batas antara tanah tempat tinggal mereka dengan batas tanah luarnya .Dengan kata lain, praktek universal untuk menyuguhkan kepada pikiran sendiri untuk suatu ruang yang akrab yang disebut “daerah kita “(we) dengan ruang lain yang lain yang asing yang disebut “daerah mereka (other)”adalah suatu cara untuk menciptakan pembedaan-pembedaan yang sepenuhnya bersifat arbriter. Bersifat arbriter karena perbedaanntara” kita” dengan “mereka”tidak mensyaratkan pengakuan “mereka” terhadap pembedaan tersebut. Cukup bagi “kita”untuk menentukan pembedaan dalam pikiran dan”mereka” menjadi “mereka” dengan sendirinya dan baik wilayah maupun status mentalitasnya (ajaranya) ditetapkan sebagai berbeda dengan wilayah dan mentalitas (ajaran) “kita” pembedaan ini kemudian disertai dengan berbagai ragam stereotype.Dengan pembedaan ini,segala macam dugaan ,asosiasi dan imajinasi tampak memenuhi “yang lain” tersebut .
Filosof perancis, Baston Bachelard ,pernah menulis suatu analisistentang apa yang disebutnya sebagai puisi ruang. Sebuah ruang obyektif – sudut, gang, kamar, loteng, dsb – jauh tidak penting dari pada apa yang di isikan dan dikenal kepadanya secara imajinatif. Ruang dalam sebuah rumah, misalnya, memperoleh suasana keakraban, kerahasiaan atau keamanan disebabkan kaarena pengalaman – pengalaman yang mengisi ruang tersebut. Dengan demikian, ruang tersebut menjadi teduh, menyeramkan atau bagaikan penjara bukan karena realitas obyektif, tapi karena pelabelan secara imajinatif. Inilah rasio Ahlusunnah Waljama'ah ketika ia memberiinilai dan arti atas no Ahlusunnah Waljama'ah sebagai “The Other” pada ahirnya, proses ini menjadi teks baku dengan apa setiap orang sunni harus melewati jaring – jaring kode ini. Kebenaran ditentukan dari penilaian intelek yang sudah terbentuk sebelumnya, bukandari materinya sendiri. istilah “bukan aswaja “ ahirnya adalah sebuah panggung yang memberi batas – batas kepada seluruh kelompok di luarnya yang jati diri dan peranannya telah ditentukan dalam imajinasi Ahlusunnah Waljama'ah.
Ahlusunnah Waljama'ah sebagai Discursive Practice
Adalah sia –sia bagi kita untuk membuktikan bahwa Ahlusunnah Waljama'ah adalah sebua paham ke-islaman yang benar. Tidak ada standar apapun yang bisa gunakan untuk menakar klaim tersebut. Sejauh runtujtan sejarah , maka kita akan menemukan bahwa yang yang terjadi sesungguhnya adalah benturan berbagai perspektif ke-islaman dimana Ahlusunnah Waljama'ah hanya salah asatu kontestannya. Kebenaran dan kesalahan hanya sebagai strategi wacana yang dikkembangkan untuk mendefninisikan diri (We) dan yang lain (Other). Pada saat sebuah wacana menjadi titik pusat, maka ia akan menjadi ukuran untuk menentukan benar dan salahnya wacana lain. Dia akan mengalami nasib yang sama dengan musuhnya jika rlasi kuasa berganti dan titik pusat di pegang oleh orang atau kelompok lain.
Dalam perspektif Culturstudies, keapaan “yang lain” (other) selalu bergantung bagaimana ia di presentasikan oleh sebuah wacana dominan Cultural studies yang mengusung semangat angti-esensialisme, menolak seluruh klaim-klaim hitam putih untuk mengesensialisasi realitas. Realitas adalah representasi. Ia di tambakan sebagai saputan kuas dankerangka wacana dominan yang menjadi titik sumbu dalam perebutaqn makna. Representasi ini di lakukan dalam rangka untuk mendevinisikan diri, membekukan identitas diri. Kebutuhan untuk menentukan identitas inilah yang kemudian melahirkan upaya untuk mencipta dan mendevinisikan yang lain ( other ).
Jadi, identitas kita (we) selalu di bangun untuk mengeksklusikan yang lain (other). Yang lain ( other) dipresentasikan sebagai negativ untuk di perlawankan dengan kita ( we ) yang positif. Yang lain salah dan kita adalah benar. Yang lain menyimpang dan kita adalah normal. Inilah yang di sebut dengan the idea of constitutive othernes, yaitu bahwa kelainan itu di cipta, didefinisikan, dipresentasikan untuk melayani identifikasi dan pengukuhan kita sebagai yang baik, benar, standar, normal, waras, dan segala atribut yang baik-baik. Keseluruhan prakter-praktek ini adalah apa yang di sebut dengan discursive practice (praktek wacana ). Sebuah wacana yang mengrung wacana lain untuk tetapmenjadi pinggiran sehingga ia bisa selalu dipersalahkan dalam rangka melayani kepentingan wacana dominan yang menjadi titik sumbuseluruh relasi kuasa ( power relation ) yang di bangun di atasnya. Tidak perlu heran bahwa Michel Foucailt mengatakan bahwa wacana berjalin berkelindan dengan kekuasaan?
Pembacaan terhadap posisi Ahlusunnah Waljama'ah juga harus kita mulai dari kesdadaran bahwa ia tidak lebih dari sekedar strategi wacana. Cara dia mendevinisikan juga di bangun dengan cara mempresentasikan yang lain sebagai salah. Oposisi bener dipakai sebagai strategi untuk menentukan keapaanya. Ini bisa dilihat dari kelompok yang di anggap menyimpang. Ahlusunnah Waljama'ah seringkali di perlawankan dengan Syi’ah, Mu’tazilah, Khawarij, dsb. Dengan melihat “definisi” yang umum di berikan terhadapnya bahwa Ahlusunnah Waljama'ah adalah kelompok yang dalam teologi mengikuti ajaran Asy’ari dan Maturidi,dalam fiqih mengikuti empat imam madzhab ( Maliki, Hanafi, Syafi’I, Hambali ) dan dalam tasawuf mengikuti Alghozali dan Junaid Albaghdadi, maka akan segera muncul satu pertanyaan yang mendasar, atas dasar apa ajaran orang-orang ini bisa di anggap sebagai Ahlusunnah Waljama'ah. Kalau aswaja merupakan satu-satunya kelompok yang mendapat jaminan keselamatan berdasarkan satu hadits tertentu, maka stansar apa yang di gunakan untuk menyebut bahwa ajaran merekalah yang benar dan akan menuai keselamatan tersebut?
Tidak ada jawaban apapun untuk mendukung klaim esensialitas kebenaran ini kecuali kalau memahaminya bahwa ini tidak lain adalah strategis wacana. Dalam strategi pewacanaan ini, maka wacana dominan ini akan menyatakan dirinya sebagai titik pusat yang menyandang klaim-klaim kebenaran, dengan apa yang lain kemudian dipresentasikan sebagai kelompok pinggiran yang menyimpang. Mu’tazilah menjadi kelompok yang sesat ketika Asy’ari mendognkelnya dari tahta dominannya. Pada saat Mu’tazilah menjadi titik pusat, Asy’ariyah aadlah sebuah wacana yang menyimpang dan sesat sebagaimana yang tergambarkan dalam peristiwa mihnah tentang status kemakhlukan Al-Qur'an.
Kalau pada awalnya, Asy’ariyah menjadi narasi kecil, maka ketika ia bergeser kepusat, ketika ia diadopsi oleh kekuasaan saat itu, ia berubah menjadi grand narative. Gerakan ‘Asy’arisme yang pada awalnya bisa dipahami sebagai proses decentering dari Grand narative Mu’tazilah, ia merubah dirinya secara sama persis dengan wacana yang dikalahkanya. Asy’ariyyah menjelma menjadi pusat penetu dari wacana-wacana yang ada . dalam hal ini , Asy’ariyyah merupakan wacana dominan yang meminggirkan wacana-wacana lain yang tidak dominan . ibarat lingkaran, Asy’ariyyah merupakan titik tengah lingkaran tersebut. Menjadi hakim untuk menentukan benar tidaknya wacana diluar dirinya. Sebagai istilah generik, yaitu Ahlusunnah Waljama'ah dalam pengertian ma ana alaihi wa ashabi, , maka setiap golongan umat Islam akan meyatakan bahwa keisalaman mereka mengikuti petunjuk rasul sebagaimana yang juga dipraktekkan oleh para sahabatnya.. syi’ah yang dituduh oleh orang Sunni tidak mengahrgai sahabat Abu Bakar , Umar dan Ustman pun mendasarkan klaim –klaim ajaranya pada Nabi dan sahabatnya. Apalagi kalau a Ahlusunnah Waljama'ah dipahami secara Universal sebagai suatu jalan Tuhan menuju kebaikan dan keselamatan, maka tidak hanya orang Islam, tapi juga orang-orang non-Muslim pun akan memiliki klaim yang sama.
“Gugatan” ini jugs kits arahkan pada upaya pendefinisian ulang yang dilakukan oleh said Agil Siraj tentang Ahlusunnah Waljama'ah sebagai manhaj Al-Qur'an-Fikr. Menurutnya, Ahlusunnah Waljama'ah adalah “cara berfikir dalam memahami agama yang meletakkan aspek tawassuth, tasamukh, (tawazun, red) sebagai pijakan dalam mencari jalan tengah.” Dari manakah manhaj ini diturunkan?. Teologi, fiqih,dan tasawuf yang selama ini diklaim sebagai suuni yang manakah yang kemudian bisa di-breakdown menjadi manhaj seperti itu? Kalau Said Agil Siraj menurunkan konsep manhaj-nya dari pemikiran Abu Hanifah, lalu bagaimana dengan pikiran tokoh-tokoh lain? Asy’ary, misalnya, dari sisi mana kita bisa menurunkannya menjadi manhaj dalam melayani kebutuhan kita saat ini. Yang justru bisa kita ambil darinya upaya decemering terhadap grand narative Mu’tazilah. Akan tetapi, ini berarti juga akan membawa kita untuk mengambil semangat yang sama dari Syiah dan khowaarij,misalnya, bahkan dari seluruh kelompok yang melakukan decentering terhadap narasi besar, tidak peduli sekte dan agama apapun. Kalau seperti ini, maka di manakah manhaj tawassuth, tasamuhk, dan tawazun yang digagas oleh said Agil Syiraj karena manhaj ini dirumuskan salah satunya dengan salah satu sentra persaingan antara Asy’ariyah dengan Mu’tazilah adalah masalah posisi rasionalitas dalam proses pemahaman atas wahyu. Dari sini, wacana Ahlusunnah Waljama'ah kemudian meminggirkan sisi rasionalitas secara sistematis dengan membunuh filsafat. Tidak lagi menjadi persoalan apakah sistem teologi Mu,tazilah dibangun diatas landasan rasionalitas sedang Asy’ariyah tidak. Masalah utama adalah kalim. Penyingkiran rasionalitas inilah yang kemudian menggiring diadopsinya sistem tasawuf Al-ghozali dan junaid Al-Qur'an Bagdadi, dan tidak akan pernah menoleh kewilayah tasawuf falsafi. Dari sini kemudian Ahlusunnah Waljama'ah sering kali disinonimkan dengan tradisi keislaman ulama salaf (ahl Al-Qur'an-Hadits yang “tidak menggunakan”akal dalam memahami Al-Qur'an ) dengan ulama kholaf (ahl Al-Qur'an-Ra’y yang menjadikan rasio sebagai instrumen untuk memahami Al-Qur'an ). Dengan cara yang sama, pemilihan empat imam mazhab sebagai sunni juga menggambarkan strstegi pewacanaan yang dilakukan oleh graand narative dalam meminggirkan wacana-wacana kecil.
Dari sinilah Aswaj kemudian penentu yang menghakimi wacana lain diluarnya. Melalui kekuatan narativenya sunni meresaf dalam sistem kekuasaan, imajinasi dan kesadaran orang sebagai centre of truth, Ahlusunnah Waljama'ah kemudian memproduksi aturan-aturan menurut caranya sendiri. Ahlusunnah Waljama'ah mendudukkan diri sebagai hakim atas setiap wacana yang ada diluarnya. Ia memvonis yang lain sebagai keluar dari main stream kebenaran.
Dari renik-renik pertarungan wacana diatas, terlihat bahwa Ahlusunnah Waljama'ah sebagai istilah tehnik yang menunjuk pada corak pemahaman tertentu atas Islam samasekali tidak memiliki pendasaran apapun atas klaimkebenarannya. Ketika ia menjadi wacana pinggiran, maka ia direpresentasikan secara negatif oleh wacana diminan. Ketika ia menjadi wacana dominan ia berganti melakukan hal yang sama. Iia membuat aturanlaindan sekaligus cara mengeksklusifkan khowarij. Sementara, manhaj tersebut dalam praktek politik sunni menjelma menjadi sikap kompromis – nepotis yang kemudian melahirkan satu adagium politik sunni yang sangat terkenal bahwa “enampuluh tahun dipilih oleh penguasa yang zalim lebih baik daripada satu malam tanpa seorang pemimpin” .
Sampai disini semakin terliahat bahwa seluruh perbincangan teentang Ahlusunnah Waljama'ah hanya sebuah romantisme naif karena memganggap bahawa Ahlusunnah Waljama'ah adalah sebuah wacanayang mutlak ideal, maka kita berusaha terus-menerusuntuk mengangkatnya sekalipun yang kita temui adalah ironi-ironi ibarat sisiffus yang terus-menerus mendorong batu kepuncak gunung sekalipun setiap kali sampai puncak setiap kali itu juga dia akan meluncur kedasar jurang. Salah-salah kita terjebak pada retorika gaya Islam modernisyang selalu berusaha selalu mencari orisinilitas sambil berteriak-teriak tahayyul, bid’ah, dan khurafat. Bisa saja ini terjadi karena didalam istilah Ahlusunnah Waljama'ah secara samar-samar terlihat imajinasi ke arah pencarian orisinalitas ini sambil menuduh selluruh orang yang berada di luarnya sebagai kelompok yang tidak selamat . konsekwensi ini bisa terjadi baik rumusan Ahlusunnah Waljama'ah sebagai isi/dogma maupun sebagai manhaj.
Tak Perlu Stempel Ahlusunnah Waljama'ah
Akan lebih sehat bagi kita untuk menjawab tantangan-tantngan masa ini tanpa harus dibebani dengan referensi sejarah masa lalu, apa lagi kalau refrensi itu berupa penjara. Dalam arti bahwa apakah kita memiliki kesadaran sebagai sunni ataukah tidak, semangat toleransi, penghormatan terhadap HAM dan upaya-upaya liberassi adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan kesetaraan gender, demokrasi dengan tanpa membedakan kewarganegaraan seseorang berdasarkan agamanya, dialog antaragama tidak harus selalu dicarikan referensi kepada Ahlusunnah Waljama'ah.
Kepada fiqh sunni manakah, baik isimaupun manhaj kita akan mencari rujukan terhadap perjuangan kita akan tegaknya kesamaan hak dan kewajiban warga negara dalam sebuah negara demokrasi? Kepada fiqih sunni yang manakah , baik isi maupun manhaj, yang akan kita jadikan rujukan bagi perjuangan kesetaraan gender. Terhadap sistem teologi yang manakah, baik isi maupun manhaj, yang akan kita jadikan rujukan dalam melaani semangat-semangat kemanusiaan yang diilhami oleh teologi pembebasan? Bukankah isu -isu kemanusiaan ini yang justru menjadi concern kita saat ini ?
Yang perlu bagi kita saat ini tidak lagi mempermak wajah Ahlusunnah Waljama'ah sedemikian rupa agar ia mampu menjawab seluruh tantangan kemanusiaan saat ini. Upaya rekontruksi Ahlusunnah Waljama'ah menjadi manhajal Fikr juga tidak cukup memadai untuk menjawab tantangan . yang perlu bagi kita adalah bagaimana keberagaman kita melahirkan sengaat untuk semakin menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tanpa mempedulikan kelompok , etnis san agamanya. Semangat ini adalh toleransi, pluralitas, HAM, demmokrasi, lingkungan hidup, dsb. Inilah yang lebih mendesak untuk kita carikan rumusannya dalam sinaran keberagaman kita dalam menegakkan HAM, demokrasi, toleransi, pluralitas, dsb, tiba-tiba kita menmemukannya sama sekali berbeda dengan Ahlusunnah Waljama'ah, baik isi maupun manhaj , ya tidak masalah. Kalau rumusan kita tidak diakui sebagai Ahlusunnah Waljama'ah, tidak usah berkecil hati karena memang tidak ada kewajiban untuk mendapatkan stempel benar dari Ahlusunnah Waljama'ah untuk memperjuangkan ini semua. Inul saja tidak berkepentingan untuk mendapat stempel halal di pantatnya dari MUI.
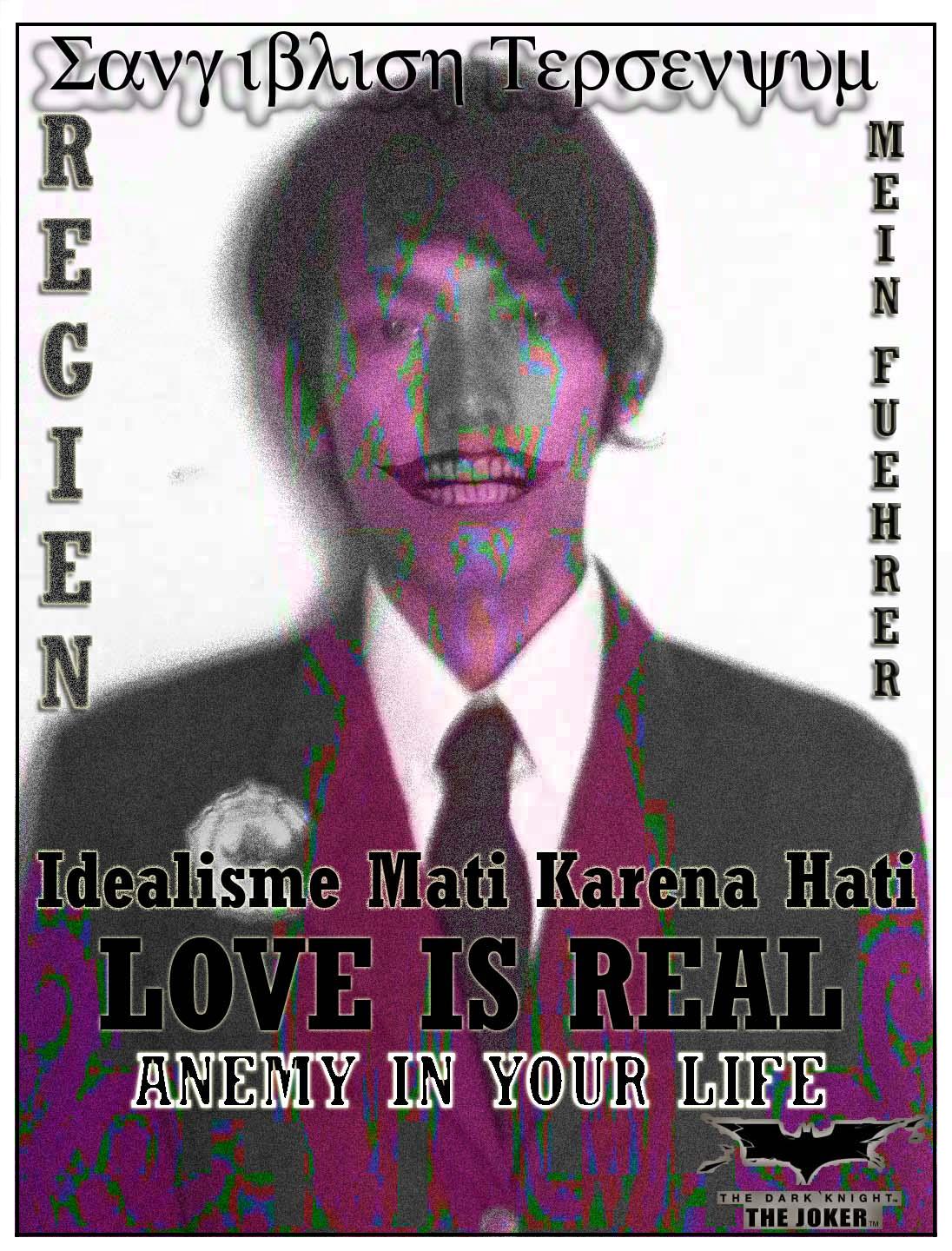

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Free Market Of ideas will make it wonderfull mind