Propaganda vs Terorisme
DALAM bukunya "Weltgeschichte der Spionage" (Sejarah Dunia Spionase, Suedwest Verlag GmbH & Co. KG, Muenchen, 1988), yang berisi agen, sistem, dan aksi spionase, seorang ahli sejarah spionase Jerman, Janusz Piekalkiewicz, menutup uraiannya dengan sebuah prediksi, "Tujuan kegiatan dinas rahasia dalam bidang spionase militer di masa mendatang adalah pengintaian potensi-potensi angkatan bersenjata lawan yang diprediksi dalam sepuluh tahun ke depan akan terjadi penemuan peralatan baru...."
Empat ratus tahun Sebelum Masehi, ahli strategi perang Cina, Sun Tzu, mengatakan, "Seratus kemenangan dalam seratus pertempuran bukanlah puncak bersejarah. Adapun seni paling tinggi adalah menekuk lawan tanpa kontak senjata." Misi "menaklukkan lawan tanpa kontak senjata" sering identik dengan misi spionase. Spionaselah yang memegang kunci agar perang dimenangkan dengan mudah, juga murah. "Wissen ist niemals zu teuer bezahlt" (tahu tidak pernah bayar mahal), itulah keyakinan Sir Francis Walsingham yang membentuk badan intelijen Inggris "Secret Service" adab XVI.
Karena kemiripan dalam sifat kerahasiaannya ("seorang dinas rahasia harus tetap rahasia." -George C. Marshall), propaganda dan terorisme sama-sama menggunakan cara-cara atau biasa memanfaatkan jasa, spionase. Bahkan dapat dikatakan, bahwa propaganda dan terorisme adalah kegiatan spionase itu sendiri.
Rupanya buku tersebut amat terilhami oleh bayangan "keberlanjutan" perlombaan senjata selama Perang Dingin; ada gambaran musuh yang nyata, teknologi dan persenjataan yang nyata, serta rencana penyerangan yang nyata pula. Bayangan perang "konvensional" seperti itu ternyata meleset, namun tidak berarti kegiatan pengintaian (mata-mata, spionase), sebagai sebuah alat bantu untuk menaklukan lawan terserah apa "lawan" didefinisikan berhenti.
Zaman berubah, seting konfrontasi global berubah. Menutup abad 20 ini Perang Dingin AS vs Uni Soviet telah berakhir, maka definisi tentang "musuh" pun perlu dipikirkan ulang, terutama bagi pemenang. Penggelindingan bola politik tata dunia dari demokrasi ke globalisasi yang dimotori AS, selain dianggap membawa optimisme bagi kemanusiaan, juga mengandung janin dan melahirkan sepasang oposisi biner baru; yang teramat serius mengancam jalannya pertumbuhan peradaban: propaganda vs terorisme. Kesannya, bukan lagi Perang Dingin penuh intrik dan selubung ketegangan, tetapi semuanya menjadi begitu kontras, vulgar, dan terbuka. Memang, ada alasan yang cukup mengapa satu negara adidaya mengambil propaganda perang "panas" ini.
Adalah The New York Times kian produktif mengusung aktualisasi makna dua kosakata (propaganda dan terorisme) ini ke hadapan publik. Sudah mafhum, kalau surat kabar ini menuding Indonesia sebagai salah satu negara sarang teroris. Dalam edisi 9 Oktober 2001 koran ini mengutip sumber Pentagon bahwa Al-Qaida mengembangkan organisasinya di tiga negara (Indonesia, Filipina, dan Malaysia) setelah Afganistan. Lagi, koran ini, edisi 16 Desember 2002, mengutip pejabat senior Pentagon ihwal perdebatan menyangkut misi propaganda rahasia militer AS di negara sahabat di Timur Tengah, Asia, dan Eropa. Di antara misi rahasia itu adalah mendiskreditkan dan meruntuhkan pengaruh masjid dan sekolah Islam, mendirikan sekolah yang didanai AS, dan mengajarkan Islam ala Amerika. Ini semua berarti, suatu awal babak baru pertempuran yang lebih vulgar, telah ditandai.
Tulisan ini tidak akan membahas sepak terjang Amrozi, Faruq, Ladin, juga Bush, ataupun Blair. Juga tidak akan terpancing dengan isi ungkapan karena itu hanyalah simbol-simbol yang fenomenal, namun membaca ada semacam skenario global sedang memperhadapkan dua isu politik global agar saling bertubrukan: propaganda vs terorisme.
Pertanyaannya, wajarkah alam kita saat ini harus diselimuti oleh dua "hantu zaman" yang mengerikan ini, sedangkan isu-isu "penyelamatan zaman" seperti dialog, toleransi, HAM, demokratisasi, dan keberadaban, baru saja gencar dikhotbahkan? Terkesan ada setting sejarah yang "dipercepat," terburu-buru. Dari mana terlihat? Jawabannya rasa-rasanya kasat mata, bahwa dampak yang ditimbulkan oleh gejala perang baru (terorisme vs propaganda) tak lagi membutuhkan dialog, pertimbangan HAM, apa itu demokrasi, berapa nyawa manusia melayang, dll, semuanya itu semacam "sudah terlampaui"; usang; tak penting lagi.
Sederhananya mungkin begini: Orang besar-kuat, tetapi penakut akan mengambil jalan propaganda, orang kecil-miskin, tetapi nekat akan menempuh jalan teror. Dua-duanya seimbang dalam memproduk ketakutan manusia dan kegelisahan peradaban.
Itulah barangkali strategi khas untuk sebuah setting peperangan yang tidak seimbang. Yang khas lagi dari keduanya adalah absen dalam dua hal: fairness dan sportivitas. Duel konvensional amat dihindari dua pihak bertikai ini. Kekuatan kecil menghadang yang besar, tentu hanya langkah fatal; kekuatan besar mengeroyok yang kecil, memalukan. Tampaknya kedua belah pihak lebih sepakat untuk "lempar batu sembunyi tangan".
Namun, semena-mena mengatakan AS sebagai penakut, rasanya kurang wajar. Lalu, mengapa AS yang adidaya itu menggelar propaganda? Jawabannya dapat dirujuk dari filsafat globalisasi itu sendiri. Tata ekonomi baru yang disebut "globalisasi" yang datang bersamaan dengan filsafat ekonomi-politik neoliberalisme memandang manusia beserta seluruh aspeknya semata-mata sebagai homo economicus (manusia ekonomi) dan menetapkannya sebagai satu-satunya model yang mendasari tindakan dan relasi manusia.
Selain menghendaki pemerintahan yang ekonomis, dialog yang ekonomis, konsep yang ekonomis, politik yang ekomonis, ekonomi yang ekonomis, perusahaan yang ekonomis, manusia-manusia ekonomis, pendek kata segala-galanya ekonomis, AS merancang perang pun harus yang ekonomis. Oleh karena itu, propagandalah satu-satunya strategi dengan biaya murah, namun hasilnya mucekil.
Di masa Perang Dingin, musuh itu riil, hanya aksinya yang abstrak. Uni Soviet itu nyata, tetapi pertempurannya lebih banyak terjadi di dunia "maya", ketegangan lebih banyak hanya dalam ilustrasi film. Intrik intelijen, perlombaan senjata, dan perebutan pengaruh (ideologi) terhadap publik dunia menjadi ciri dominan. Tidak ada perang konvensional terbuka kapitalis vs komunis, AS vs Uni Soviet, di masa itu. Itu terjadi karena masing-masing senantiasa berhitung. Kekuatan militer kedua belah pihak hampir seimbang. "Peperangan" lebih banyak berkecamuk di urat syaraf.
Kapitalisme akhirnya memenangkan game ini, tetapi sebenarnya kekalahan Uni Soviet bukan oleh AS, tetapi oleh negara lain karena tenaga Uni Soviet habis terkuras setelah Negeri Beruang itu nekat melakukan invasi militer ke Afganistan. Tinggallah AS juara sendirian, tidak ada lawan. Lalu, ada gravitasi subjektif, mungkin berlaku ujub atas kebolehannya sendiri, "Persis reaksi koboi setelah menembak jatuh lawannya: memutar-mutar pistol dan lalu menyarungkannya. Seekor ayam jantan akan berkokok setelah musuhnya lari" (Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, Bandung: Mizan, 1997). Francis Fukuyama segera "menarikan" pena dengan the end of history-nya, bahwa ujung Perang Dingin telah sekaligus mengantarkan kepada akhir sejarah dan "bahwa dunia ditakdirkan semakin mirip dengan Barat" (visi global Hans Kohn dan Robert Emerson). Benarkah demikian?
Gambarannya sama sekali jauh berbeda. Dalam wacana strategi: tidak ada lawan, berarti kemunduran. Untuk maju, suatu bangsa membutuhkan musuh. Bisa berupa bangsa, kelompok agama, atau sekadar persepsi artifisial, yang karenanya seluruh gerbong bangsa terpacu menghadapinya. Yang penting di sini adalah, ada satu simbol yang dianggap sebagai common enemy (musuh bersama). Ketika lawan riil tidak ada, diciptakanlah lawan dalam bayangan, sebut saja "Perang Panas" (mengambil analogi terbalik dari Perang Dingin). Suatu sindiran yang barangkali tak jauh beda dari buku Enemy in The Mirror, karya Roxanne L. Euben (Princeton University Pres, 1999); berperang melawan persepsi yang adalah ciptaannya sendiri.
Berbeda dari Perang Dingin, di masa Perang Panas ini, aksinya riil, tetapi musuhnya yang abstrak. Produk terorisme sebagaimana juga produk propaganda adalah nyata, terasa; sekian orang mati, sekian miliar kerugian material, sekian bangunan luluhlantak, bahkan bisa melenyapkan sebuah negeri dari peta. Akan tetapi, pelakunya atau sekurangnya "alasannya," masih abstrak. Meski ada di sana disebutkan nama si Anu atau Si Fulan sebagai pelaku, dalam tataran publik, tetap saja ragu. Khasnya kerja dunia serbarahasia, seperti propaganda dan terorisme, adalah memproduk bias persepsi dan mengidap ketidakjelasan inheren; ada sesuatu yang disembunyikan; sesuatu yang lebih penting dan berharga ketimbang yang diedit ke permukaan.
Artinya, jangankan sekadar mengutip "seorang pejabat Pentagon" pernyataan resmi negara pun belum tentu apa yang sebenarnya. Ini karena, baik propaganda maupun terorisme, bekerja dengan agendanya sendiri. Sebuah agenda di luar kebiasaan nalar wajar. Kerahasiaan inilah yang membuat kabur persepsi, publik kehilangan konteks antara tujuan sebenarnya dan aksi masif destruktif yang tampak.
Itulah model perang akhir zaman, teramat sungkelit untuk dipahami. Meminjam istilah Jakob Sumardjo dalam artikel "Puisi Kalekatu" ("PR", 10/12/2002), perang model ini seperti kalekatu, binatang kecil sejenis laron yang suka terbang atau meloncat sehingga sulit ditangkap. Juga lamat-lamat ada sedikit "irisan" dengan pendapat Roxanne L. Euben untuk bidang politik, bahwa "masalah khusus dari teori politik adalah bagaimana caranya membentuk suatu masyarakat yang tanpa perlu fondasi transenden yang menunjang." Suatu bangunan masyarakat politik "pascafondasional" (istilah Euben sendiri) yang menolak segala fondasi sakral, merasa lebih nyaman dengan hasil imajinasi.
Ada semacam tren: orang-orang pascamodern meninggalkan yang fakta dan lebih menyukai yang imaji. Apakah manusia kini sudah bosan dengan realitas kasat mata? Bahkan orang sudah membayangkan, perang zaman ini sejatinya adalah perang wacana; adapun korban jatuh, gedung runtuh, itu hanya fakta semacam "bumbu penyedap" saja, ornamen pemanis dari sebuah skenario.
Kini, di alam kita, konsep the clash of civilization-nya Samuel Huntington juga harus direvisi. Karena hanya benar selama menyangkut hal-hal nonfisik, tidak ada lagi perang kolosal seperti halnya Perang Salib, yang menghadapkan dua pasukan dalam kontak bersenjata, Kristen vs Islam, dimulai 1099 M.
Akan tetapi, apakah makna praktis "terorisme" dan "propaganda" bagi kita orang awam? Kita pada umumnya meyakini, baik terorisme maupun propaganda, keduanya adalah jalan yang tidak wajar/normal. Terorisme menerjang lawan dari belakang secara culas; propaganda mengintimidasi lawan, termasuk membohongi publiknya sendiri. Kedua cara ini dikutuk baik oleh agama ataupun nurani kemanusiaan. Hanya orang-orang yang kerdil dan tak berperikemanusiaan sajalah yang sanggup menjalankan dua strategi ini. Sebuah rivalitas artifisial, keduanya saling berhadapan dalam aksi-aksi masif menghebohkan tanpa kita tahu -- dengan yakin -- siapa sebenarnya yang menjadi pelaku.
Pada dasarnya terorisme adalah sebentuk propaganda juga, sedangkan propaganda bisa merupakan sebentuk teror. Kini bukan lagi perang ideologi, tetapi perang persepsi. Suatu aksi biasa bisa diversi teror oleh propaganda, yang bukan propaganda bisa dibikin propaganda oleh teror. Peran media massa dalam hal ini amat dominan. Itulah barangkali jawaban mengapa The New York Times berperan sedemikian rupa.
Sampai kapan perang ini akan berakhir? Mari kita sama-sama bertanya kepada Ki Dalang.***
Pikiran rakyat, senin 6 Januari 2003
Penulis adalah alumni Univ. Braunschweig, Jerman, 1993, kini bekerja di bagian Personel & Org. Dev. SBU Helikopter, PT Dirgantara Indonesia Bandung.
Rekan-rekan Yth.
Berikut adalah ide2 propaganda yang menekankan agar Pemilu
bebas dari okum, cara2, dan pengaruh Orba.
Propaganda ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran
politik masyarakat akan pentingnya mewujudkan pemerintahan
baru yang hanya bisa terwujud melalui Pemilu yang bebas Orba.
Jadi, meskipun masih terdapat pro kontra akan kesahihan
Pemilu yg dilaksanakan oleh rejim Habibie yg tidak legitimate
dan spekulasi keberhasilan pemilu nanti, yang terpenting
adalah meningkatkan kesadaran politik masyarakat sehingga
bisa mengambil keputusan sendiri harus apa dan bagaimana
dalam menyikapi Pemilu nanti.
Bagi rekan2 seperjuangan yang sevisi, dimohon partisipasinya
untuk masing-masing mengimplementasikan propaganda tersebut
dalam berbagai bentuk yang bisa menyampaikan pesan tersebut
ke publik secara luas, khususnya dari lingkungan sehari-hari
di kantor, klien, kampus, ataupun rumah tangga.
Mengingat biayanya akan sangat besar jika ditanggung satu pihak,
sangat diharapkan masing2 pihak berkontribusi sesuai kemampuannya
untuk mencetak/memproduksi sendiri alat propagandanya.
Materinya bisa diambil atau dikembangkan dari alternatif2 di bawah
ini. Yg penting, ide dasarnya adalah: SAPU BERSIH ORDE BARU,
baik itu cara-cara berpikirnya, cara bertindaknya, kemunafikannya,
kejahatan politiknya, birokrasinya, ketegaannya menyengsarakan
rakyat, sampai oknum dan antek2nya, baik individu maupun organisasi.
Bentuk2 media propaganda tsb al.:
1. Barang cetakan: stiker, spanduk, poster, kaos, badge
2. Banner Ad di internet, signature email anda
3. Iklan di media cetak
dll
Duncan Hallas 1984
Agitasi dan propaganda
(September 1984)
________________________________________
Sumber: What do we mean by ...?, Socialist Worker Review, No.68, Sep 1968, hlm.10;
Disalin & diberi tanda baca oleh Einde OCallaghan untuk Marxists Internet Archive;
________________________________________
Menurut kamus Oxford, mengagitasi adalah “membangkitkan perhatian (to excite) atau mendorong (stir it up)”, sedangkan propaganda adalah sebuah “rencana sistematis atau gerakan bersama untuk penyebarluasan suatu keyakinan atau doktrin.
Definisi ini bukan merupakan titik pijak yang buruk. Agitasi memfokuskan diri pada sebuah isu aktual, berupaya ‘mendorong’ suatu tindakan terhadap isu tersebut. Propaganda berurusan dengan penjelasan gagasan-gagasan secara terinci dan lebih sistematis.
Seorang marxis perintis di Rusia, Plekhanov, menunjukkan sebuah konsekuensi yang penting dari pembedaan ini. “Seorang propagandis menyajikan banyak gagasan ke satu atau sedikit orang; seorang agitator menyajikan hanya satu atau sedikit gagasan, tetapi menyajikannya ke sejumlah besar orang (a mass of people)”. Seperti semua generalisasi yang seperti itu, pernyataan di atas jangan dipahami secara sangat harfiah. Propaganda, dalam keadaan yang menguntungkan, bisa meraih ribuan atau puluhan ribu orang. Dan ‘sejumlah besar orang’ yang dicapai oleh agitasi jumlahnya sangat tidak tetap. Sekalipun demikian, inti dari pernyataan Plekhanov itu memiliki landasan yang kuat (sound).
Banyak gagasan ke sedikit orang
Lenin, dalam What is to be done, mengembangkan gagasan ini:
Seorang propagandis yang, katakanlah, berurusan dengan persoalan pengangguran, mesti menjelaskan watak kapitalistis dari krisis, sebab dari tak terhindarkannya krisis dalam masyarakat modern, kebutuhan untuk mentransformasikan masyarakat ini menjadi sebuah masyarakat sosialis, dsb. Secara singkat, ia mesti menyajikan “banyak gagasan”, betul-betul sangat banyak, sehingga gagasan itu akan dipahami sebagai suatu keseluruhan yang integral oleh (secara komparatif) sedikit orang. Meskipun demikian, seorang agitator, yang berbicara mengenai persoalan yang sama, akan mengambil sebagai sebuah ilustrasi, kematian anggota keluarga seorang buruh karena kelaparan, peningkatan pemelaratan (impoverishment) dsb., dan penggunaan fakta ini, yang diketahui oleh semua orang, akan mengarahkan upayanya menjadi penyajian sebuah gagasan tunggal ke “massa”. Sebagai akibatnya, seorang propagandis bekerja terutama dengan mamakai bahasa cetak; seorang agitator dengan memakai bahasa lisan.
Mengenai pokok pikiran yang terakhir, Lenin keliru, karena ia terlalu berat-sebelah. Seperti yang ia sendiri nyatakan, sebelum dan sesudah ia menulis pernyataan di atas, sebuah surat kabar revolusioner bisa dan mesti menjadi agitator yang paling efektif. Tetapi ini merupakan masalah sekunder. Hal yang penting adalah bahwa agitasi, apakah secara lisan atau tertulis, tidak berupaya menjelaskan segala sesuatu. Jadi kita menyatakan, dan mesti menyatakan, bahwa para individu buruh tambang yang menggunakan pengadilan kapitalis untuk melawan NUM adalah buruh pengkhianat, bajingan (villains), dipandang dari segi perjuangan sekarang ini; betul-betul terpisah dari argumen umum tentang watak negara kapitalis. Tentu kita akan mengajukan argumen, tetapi kita berupaya ‘membangkitkan perhatian’, ‘mendorong’, ‘membangkitkan rasa tidak senang dan kemarahan’ terhadap pengadilan di sebanyak mungkin buruh. Ini mencakup mereka (mayoritas besar) yang belum menerima gagasan bahwa negara, negara apapun dan pengadilannya, pasti merupakan sebuah instrumen dari kekuasaan kelas.
Atau ambil sebuah contoh lain. Lenin berbicara tentang “ketidakadilan yang amat parah” (crying injustice). Namun, sebagai seorang pengikut Marx yang mendalam, ia betul-betul mengetahui bahwa tidak ada ‘keadilan’ atau ‘ketidakadilan’ yang terlepas dari kepentingan kelas. Di sini, ia menunjuk dan berseru pada kontradiksi antara konsep ‘keadilan’ (‘justice’ or ‘fairness’) yang dipromosikan oleh para ideolog masyarakat kapitalis dengan realitas yang terekspos dalam perjalanan perjuangan kelas. Dan hal itu mutlak benar dari sudut pandang agitasi.
Seorang propagandis, tentu saja, mesti menyelidiki secara lebih mendalam, mesti meneliti konsep keadilan, perkembangan dan transformasinya melalui berbagai masyarakat berkelas yang berbeda, isi kelasnya yang tak terhindarkan. Tetapi hal itu bukan merupakan tujuan utama dari agitasi. Para ‘marxis’ yang tidak memahami pembedaan ini menjadi korban dari ideologi borjuis, menjadi korban dari generalisasi yang lepas dari konteks waktu (timeless generalisations), yang mencerminkan masyarakat berkelas yang diidealisasikan. Yang paling penting, mereka tidak memahami secara konkrit bagaimana sebenarnya sikap kelas buruh berubah. Mereka tidak memahami peran pengalaman, sebagai contoh, pengalaman tentang peran polisi dalam pemogokan para buruh tambang. Mereka tidak memahami perbedaan antara agitasi dan propaganda.
Kedua hal itu penting, sangat diperlukan, tetapi keduanya tidak selalu bisa dikerjakan. Agitasi memerlukan kekuatan yang lebih besar. Tentu saja seorang individu terkadang bisa mengagitasi sebuah keluhan tertentu secara efektif, katakanlah, keluhan mengenai kurangnya sabun atau tissue toilet yang layak di sebuah tempat kerja tertentu, tetapi sebuah agitasi yang luas dengan sebuah fokus yang umum tidaklah mungkin tanpa sejumlah besar orang yang ditugaskan dengan pantas untuk melaksanakannya, tanpa sebuah partai.
Jadi apa pentingnya pembedaan tersebut sekarang ini? Untuk sebagian besar, para sosialis di Inggris tidak berbicara ke ribuan atau puluhan ribu orang. Kita sedang berbicara ke sejumlah kecil orang, biasanya berupaya meyakinkan mereka (to win them) melalui politik sosialis yang umum, dan bukan melalui agitasi massa. Jadi apa yang kita usulkan (arguing) pada dasarnya adalah propaganda. Tetapi di sinilah kebingungan muncul. Karena terdapat lebih dari satu jenis propaganda. Ada sebuah pembedaan antara propaganda abstrak dan jenis propaganda yang diharapkan dapat mengarah ke suatu aktivitas, yaitu propaganda yang konkrit atau realistik.
Propaganda abstrak memunculkan gagasan yang secara formal benar, tetapi tidak terkait dengan perjuangan atau dengan tingkat kesadaran yang a
da di antara mereka yang menjadi sasaran dari penyebaran gagasan itu. Sebagai contoh, menyatakan bahwa di bawah sosialisme sistem upah akan dihapuskan adalah mutlak benar, menempatkan usulan yang seperti itu kepada para buruh sekarang ini bukanlah agitasi, melainkan propaganda dalam bentuk yang paling abstrak. Begitu pula, usulan terus-menerus (constant demand) untuk sebuah pemogokan umum, terlepas dari apakah prospek untuk melakukannya bersifat riil dalam situasi yang sekarang, mengarah tidak ke agitasi, melainkan ke penarikan diri (abstaining) dari perjuangan yang riil di sini dan sekarang.
Di sisi lain, propaganda realistis berpijak dari asumsi bahwa kelompok-kelompok sosialis yang kecil tidak dapat secara meyakinkan mempengaruhi kelompok-kelompok buruh yang besar sekarang ini di hampir setiap keadaan. Tetapi hal itu juga mengasumsikan bahwa terdapat argumen tentang isu-isu spesifik, yang dapat dicoba untuk dibangun oleh para sosialis. Jadi seorang propagandis realistis di sebuah pabrik tidak akan mengusulkan penghapusan sistem upah. Ia (laki-laki atau perempuan) akan mengusulkan serangkaian tuntutan yang diharapkan dapat mengarahkan perjuangan ke kemenangan, dan sudah tentu melebihi kemenangan kecil (tokens) yang diberikan oleh bikorasi serikat buruh. Jadi mereka akan mengusulkan, misalnya, peningkatan ongkos rata-rata setiap produk (a flat rate increase), pemogokan mati-matian dengan tuntutan penuh (the full claim, all out...strike) dan bukan pemogokan yang selektif, dsb.
Menyeimbangkan agitasi dengan propaganda secara benar (Getting the balance right)
Semua ini bukanlah agitasi dalam arti yang dibicarakan oleh Lenin, hal itu adalah satu atau dua orang sosialis yang memunculkan serangkaian gagasan tentang bagaimana untuk menang. Tetapi hal itu juga bukan propaganda abstrak karena hal itu terkait dengan sebuah perjuangan yang riil dan karenanya bisa terkait dengan minoritas buruh yang cukup besar di suatu wilayah. Ini berarti bahwa propaganda realistis dapat membangun hubungan (strike a chord) dengan sekelompok orang yang jauh lebih besar daripada mereka yang sepenuhnya terbuka untuk gagasan-gagasan sosialis. Bahwa sekarang ini hanya sekelompok orang yang sangat kecil yang akan terbuka untuk semua gagasan-gagasan sosialisme. Kelompok yang lebih besar tidak akan seperti itu, tetapi masih bisa menerima banyak propaganda dari kaum sosialis untuk tidak mempercayai para pejabat, untuk mengorganisir di lapisan bawah (the rank and file) dan sebagainya.
Pentingnya pembedaan ini ada dua (twofold). Para sosialis yang mempercayai bahwa mereka harus melakukan propaganda di kelompok-kelompok diskusi mereka yang kecil, dan mengagitasi di tempat kerja mereka, sangat mungkin menaksir terlalu tinggi (overestimate) pengaruh mereka di sejumlah besar buruh dan dengan demikian kehilangan kesempatan untuk membangun basis di sekitar sejumlah kecil pendukung. Mereka yang percaya bahwa mereka hanya harus melakukan propaganda abstrak dalam diskusi-diskusi mereka dengan para sosialis yang lain dan di tempat kerja mereka bisa mengambil sikap menarik diri ketika perjuangan yang riil benar-benar meletus.
Dengan melakukan propaganda realistis pada sebuah periode di mana agitasi massa secara umum tidak mungkin, kaum sosialis akan jauh lebih mungkin untuk dapat menghindari kedua jebakan tersebut.
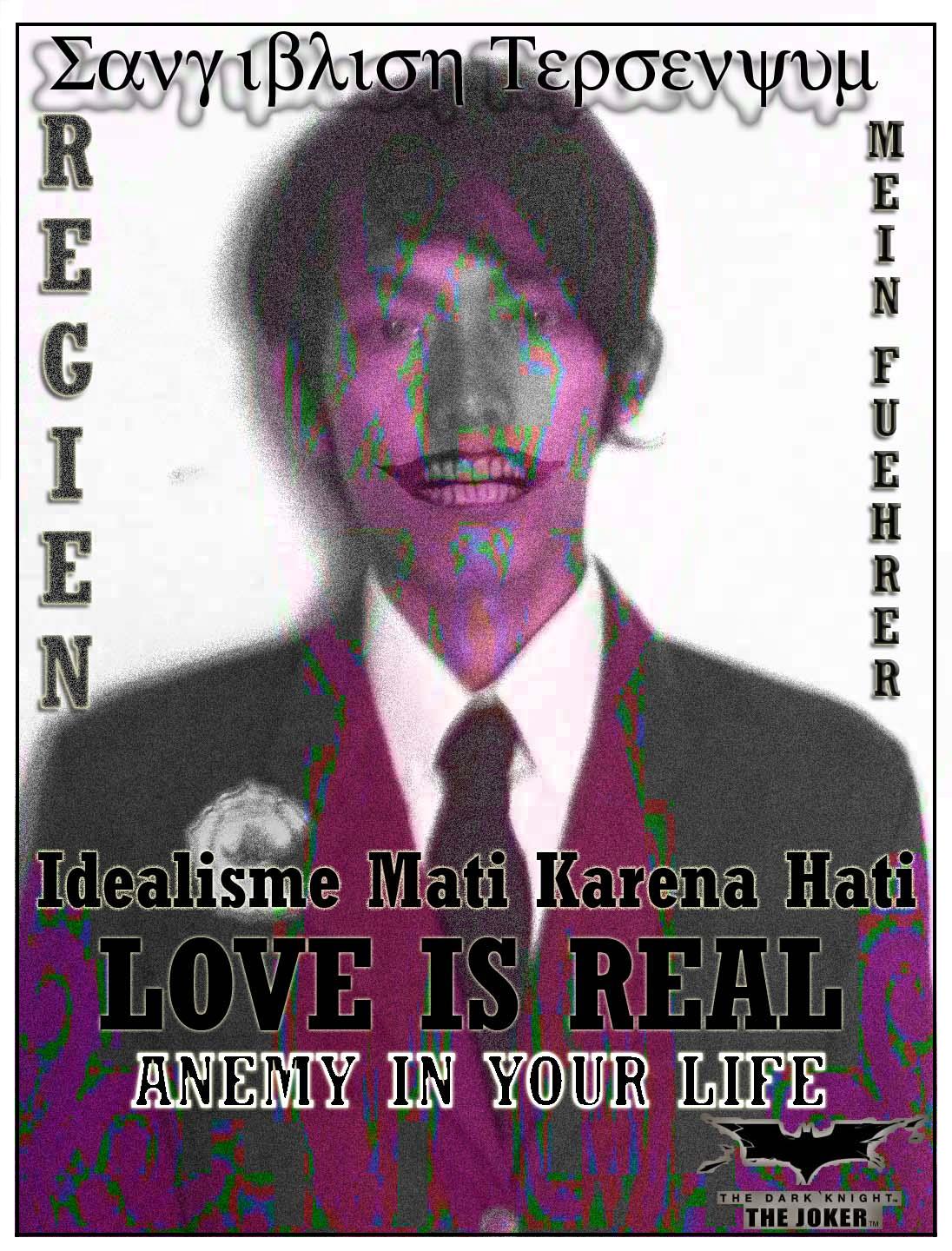

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Free Market Of ideas will make it wonderfull mind